Kesusatraan Melayu Tionghoa merupakan kumpulan karya sastra yang dihasilkan oleh kaum peranakan Tionghoa. Sejarah keberadaan karya sastra ini sudah dimulai sejak tahun 1870. Bahkan sastra ini telah muncul jauh sebelum sastra modern Indonesia mulai semarak. Menurut Caludine Salmon, selama hampir 100 tahun (1870-1960) telah terdapat 3005 buah karya sastra yang dihasilkan oleh 806 penulis. Sementara enurut Prof. Dr. A. Teeuw, selama hampir 50 tahun (1918-1967), sastra modern Indonesia hanya terdiri dari sekitar 400 karya yang dihasilkan oleh 175 penulis.
Namun sayangnya kumpulan karya sastra ini kurang mendapat pengakuan. Sastra ini dianggap baru muncul setelah masa Perang Dunia I, yaitu pada 1918, ketika Balai Pustaka yang membentuk Dewan Redaksi untuk mendorong kegiatan menulis di kalangan orang Indonesia.
Banyak tokoh yang berpendapat tentang pentingnya Kesusastraan Melayu Tionghoa dalam perkembangan sastra Indonesia. Ni Joe Lan, seorang editor majalah Ekng Po (1928) dan Sin Po (1935), menamai sastra ini sebagai Kesusastraan Indo-Tionghoa ayng berkembang di luar lembaga resmi. Pramoedya Ananta Toer menyebut masa perkembangan sastra ini sebagai masa asimilasi, masa transisi dari sastra lama ke sastra baru. Pada tahun 1971, C.W. Watson juga menyebutnya sebagai pendahulu Kesusastraan Indonesia.
Kini kumpulan sastra ini diterbitkan kembali dalam bentuk buku oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Koleksi buku Kesusatraan Melayu Tionghoa terdiri dari 25 jilid dengan total sekitar 15.000 halaman. Karya sastra dan tulisan yang telah dipilih, dinilai dapat menunjukan peranan masyarakat peranakan Tionghoa dalam proses terbentuknya kebangsaan Indonesia.
Menurut penyusun buku, karya sastra ini banyak menggambarakan segmen kondisi kehidupan kaum peranakan Tionghoa dari sebelum jaman Perang Dunia II. Satra ini sarat dengan ajaran moral dan perignatan-peringatan yang ditujukan untuk kaum wanita. Peringatan ini sesuai ajaran konfusius, seperti wanita harus menuruti orang tuanya dan suaminya, dan peringatan lain yang mengkritik cara berpakaian budaya barat.
Saat ini buku ini telah ditulis dengan ejaan yang baru, seperti misalnya huruf ”dija” ditulis menjadi “dia” dan huruf “njang” ditulis menjadi “yang”. Meskipun begitu ada kemungkinan ejaan tersebut memiliki penggunaan dan interpretasi yang berbeda dari maksud si penulis. Sementara bahasa yang digunakan masih mengacu pada gaya bahasa aslinya tanpa perubahan, seperti “Sebenernya saya perlu dateng kemari aken minta tulung pada tuan”. Di sini saya lampirkan salah satu karya sastra yang pernah saya baca, yaitu cerpen mengenai Tahun Baru Cina yang diambil dari buku Kesusastraan Melayu Tionghoa jilid 4.
Disadur dari : Kesusastraan Melayu Tionghoa Jilid 1.“Bagaimana Empe Tjoe Sudah Rayaken Taon Baru dengan Penuh Kagirangan”Diterjemahkan dari buku “Kesusasteraan Melayu Tionghoa” karya Kwee Tek Hoay.Aku punya seorang kenalan lama namanya Lauw Ay Tjoe. Dulu ia termasuk dalam salah satu dari orang-orang Tionghoa yang paling kaya di Mauk, dan ia punya lima anak - tiga lelaki dan dua perempuan - semua belajar di sekolah Inggris atau di Tiong Hoa Hak Tong, dan malah anak lelakinya yang paling besar sudah melanjutkan sekolahnya pada St. Joseph School di
Singapura, sedang dua yang lain sudah tamat dari Methodist Scholl di Buitenzorg. Ketiga anak lelakinya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan: yang pertama menjadi guru Inggris pada salah satu Haktong di Semarang, yang kedua bekerja pada sebuah firma Inggris di Surabaya, dan yang ketiga pada satu firma Tionghoa di Medan, dan dua diantaranya sudah
beristri. Kedua anak perempuannya, cuma belajar di Hak Tong sampai kelas V, semua sudah menikah: yang pertama ada di Bandung, suaminya membuka toko kain tenun, dan yang kedua ada di Cirebon, suaminya bekerja sebagai guru pada satu Hak Tong.
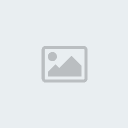
Seperti halnya orang lain, beberapa tahun yang lalu, berhubung dengan jatuhnya harga beras dan padi, Lauw Ay Tjoe mengalami kerugian besar hingga kekayaannya melarat, meski tidak ludes semuanya. Lantaran berhati-hati, bekerja rajin dan hidup sederhana, maka meskipun sekarang hidupnya susah, ia tidak pernah kekurangan: warungnya masih bisa memberi
keuntungan yang cukup untuk ia makan; selain itu ia masih punya beberapa petak tanah yang ditanami kelapa, jagung dan sayur-sayuran, serta ia juga memelihara babi, domba dan kambing ypiaraan, sedang hasil dari telor ayam dan bebek yang dipelihara dan diurus oleh istrinya, membuat ia bisa menabung sejumlah uang.
Memang kalau dibandingkan dengan kekayaannya waktu dulu, Ay Tjoe sekarang bukan seorang hartawan lagi; kekayaannya yang lenyap itu tidak membuat ia menyesal, karena sekarang tanggungannya pun sudah ringan: anak-anaknya sekarang sudah besar dan bisa mencari makan sendiri serta mempunyai penghidupan yang layak, sedang penghasilannya tidak hanya saja cukup untuk hidup sederhana, malah masih bisa ia sisihkan. Kalau ada satu hal yang membuat Empe dan Uwa Ay Tjoe berduka, itu lantaran semua anak-anaknya berada di tempat yang jauh sehingga tidak mudah bagi mereka bedua untuk pergi menengok mereka dan menggendong cucu-cucunya.
Seperti halnya orang-orang Tionghoa lain yang tinggal dalam desa di daerah Jawa Kulon, Ay Tjoe dan istrinya terhitung konservatif, sangat kukuh pada segala aturan kuno. Adat kebiasaan yang sudah lama dilupakan orang-orang di kota, masih ia dekap dengan keras. Hal ini bisa dibuktikan pada setiap tahun baru Imlek. Pintu-pintu dan jendela-jendela ditempeli dengan kertas merah yang dinamakan Mui-Tui (penjaga pintu), di atasnya tertulis huruf-huruf Tionghoa besar yang berarti keselamatan, murah rejeki dan sebagainya. Di atas altar abu leluhur pun, terdapat berbagai macam sajian lengkap yang biasa tampak dalem rumah-rumah orang Tionghoa pada 40 tahun lalu, seperti susunan kue Tjina (kue kranjang), buah kingkip yang ditusuk diatas papan yang dicat merah bercampur air emas (tjin-ap), buah jeruk besar dengan dikelilingi oleh buah srikaya (buah minta lekas kaya), kue Hwat yang dibiarkan sampai bulukan karena baru diangkat saat Cap-Gomeh selesai., dan berbagai macam sajian lainnya. Meski dalam kehidupan sehari-hari dia agak pelit dan sederhana, tapi setiap kali sembayangan abu leluhur, apalagi dekat Cia-Gwee (tanggal satu bulan satu Imlek), makanan dan kue-kue yang disajikan serba lengkap, di malam tahun baru dan Ciagwee Ceekauw, ia tidak sungkan untuk membakar beberapa gulung petasan kong-sun-paw dan memanggil topeng, lenong dan musikk tanjidoor yang datang memberi selamat; Ia pegang kebiasaan sembahyang Tuhan Allah di malem Ciagwee Ceekauw (tanggal sembilan bulan satu Imlek), dan terkadang juga membuat sembahyang buat sam-kay-kong, dimana ia undang tetangga-tetangganya untuk turut makan dan minum serta main kartu.
Semua aturan dan kebiasaan ini bukan cuma dilakukan dulu ketika ia masih jadi hartawan, dalam tahun-tahun belakangan pun ia jalankan terus; celengan dari istrinya yang dikumpulkan dari uang penjualan telur, selalu digunakan untuk merayakan tahun baru, yang ia anggap sebagai suatu keharusan yang tidak boleh disingkirkan. Ia merasa sudah lebih dari cukup menderma f 0,50 ketika di Mauk orang melakukan penggalangan dana guna Roodekruis Fonds (sumbangan palang merah), berhubung dengan peperangan di Shanghai di tahun 1932; tapi ia merasa tidak puas kalau di malam Ciagwee Cee-it (tanggal satu bulan satu) ia tidak membakar sedikitnya dua tiga renteng petasan gulungan besar.
Keroyalan yang luar biasa setiap merayakan tahun baru ini membuat aku dan tetangga-tetangga lain Ay Tjoe, setiap malam Ciagwee Cee-it biasa berkumpul di rumahnya, makan-minum, menonton pertunjukan, dan main soe-sek atau domino. Pada malam Imlek tahun lalu pun, aku singgah ke tempatnya : semuanya berjalan seperti biasa, tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, malah makanannya lebih banyak dan ikan bandeng pindang yang ia suguhkan di atas meja makan lebih besar dari dulu, karena katanya harga ikan di pasar malam sangat murah. Tapi toh meski begitu dari raut muka Ay Tjoe dan istrinya tampak rasa penyesalan dan kurang senang yang tidak bisa disembunyikan, dan aku tahu penyebabnya : dari kelima anaknya, empat menantu, dan dua belas cucu,
tidak satupun yang muncul di malam tahun baru;
tidak satupun yang turut ambil bagian dalam sembahyangan pada abu leluhur; dan
tidak satupun yang datang untuk menghaturkan selamat kepada ayah dan ibu atau ema dan engkong!
Ini adalah satu hal yang baru, karena di tempo dulu, ketika anak-anak masih sekolah, biarpun ada yang sekolah di Singapura, selalu pulang menjelang tahun baru untuk berkumpul bersama orang tua, dimana teriakan dan suara tawa gembira dari kelima anak itu membuat rumah Ay Tjoe menjadi terliput oleh suasana bahagia, apalagi kalau ke lima saudara itu menyanyikan berbagai macam lagu dan nyanyian Inggris atau Tionghoa dengan diiringi oleh biola dan gitar. Tahun-tahun belakangan ketika anak-anak sudah bekerja dan tinggal di tempat lain, meski tidak semuanya bisa berkumpul, sedikitnya ada dua yang pulang ke Mauk ketika dekat tahun baru, dan keduanya, bersama beberapa anaknya sudah cukup membuat rumah Ay Tjoe menjadi hangat dan ramai.
Dan tentu saja diantara teman-teman dan tetangga yang datang ke rumah Ay Tjoe ada banyak yang bertanya, kenapa tidak ada satupun anak-anaknya yang pulang. “Ya, apa boleh buat” Ay Tjoe menyahut dengan paras duka sambil menarik nafas; “Si Dorci yang ada di Bandung kedua anaknya sedang sakit : encinya yang di Cirebon lagi hamil sudah sampai bulannya, hampir bersalin; si Ing Hoa yang di Semarang barangkali bisa datang waktu hampir Capgomeh tapi itu pun belum tentu; yang di Surabaya bilang tidak bisa, sebab terlalu sibuk dengan pekerjaannya; yang di Medan tidak ada kabar ceritanya sama
sekali.”
Bagi yang sudah mengenal baik tabiat dan kebiasaan Ay Tjoe, lantas bisa mengerti bagaimana jengkelnya perasaannya. Makanan begitu banyak, jeruk Cina, buah anggur, dan biskuit Ho-Ho yang ia beli di pasar malam, semua akan masuk ke dalam perut orang lain, dimakan oleh anak-anak tetangga, bukan oleh anak-anak dan cucunya sendiri.
Lebih kasihan lagi ketika Capgomeh tiba dan tidak ada satupun dari anak-anaknya datang buat tengok orang tuanya, karena yang di Semarang “ada halangan”, yang di Bandung anaknya masih sakit, dan yang di Cirebon baru melahirkan anaknya di malam Ciagwee Ceegouw (tanggal lima bulan satu Imlek). Tidak heran kalau Ay Tjoe pernah bilang padaku : ”Ini tahun Ciagwee kelewat sepi dan tidak enak sama sekali”.
Ini kejadian pada tahun yang lalu, Kwie Yoe 2484.
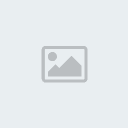
Dan bagaimanakah sekarang ?
Tanggal 1 Ciagwee yang akan datang, Kak Soet 2485, oleh Ay Tjoe bakal dirayakan secara ramai seperti belum pernah terjadi seumur hidupnya. Ia punya lima anak, empat menantu dan empat belas cucu (karena sudah bertambah lagi 2 cucu) sekarang sudah berkumpul semua di Mauk, hingga bangsal samping yang biasa dipakai menyimpan padi dan kelapa sekarang dijadikan kamar-kamar tidur karena di rumahnya sudah terlalu penuh.
Bagaimana bisa begitu ?
Dalam setahun krisis yang mengamuk hebat ini membuat ke lima anak itu terpaksa balik dan tinggal sama orang tuanya. Ayng paling dulu datang yang lelaki dari Medan yang belum menikah, yang pada bulan Juni telah balik ke Mauk lantaran firma dimana ia bekerja telah gulung tikar dan tidak bisa dapat pekerjaan lain di Medan; di bulan Agustus anak lelaki yang di Surabaya pun datang bersama anak istrinya, diberhentikan dari pekerjaannya. Di bulan September datang juga anak perempuannya dan suaminya dari Cirebon dengan kelima anaknya, karena gaji suaminya hendak diturunkan dari f125 jadi f75, rasanya tidak cukup dengan gaji begitu untuk menghidupi istri dan kelima anaknya, hingga lantas pindah bekerja di ahktong Tangerang dengan bayaran f90, dan ia menumpang tinggal di rumah mertuanya supaya ongkos jadi ringan. Yang jadi guru di Semarang pun pulang ke rumah orang tua bersama anak istrinya karena Haktong tempat ia bekerja selalu menunggak gajinya, maka ia sudah melamar pekerjaan lagi pada satu Haktong di Batavia yang kepalanya berjanji mau memakinya pada bulan Maret. Anak perempuan yang di Bandung pun terpaksa pulang ke Mauk lantaran suaminya sudah jatuh pailit, dan ia bakal menggantikan Ay Tjoe untuk mengurus warung.
Di jumat tanggal 9 Februari, tiga hari menjelang Pasar Malam, aku jalan-jalan ke rumah Ay Tjoe yang sedang duduk dikerubungi oleh enam cucu-cucu, dua diantaranya duduk dipangkuannya.“Wah, sibuk betul sekarang” aku menegur. “Perkara sibuk jangan ditanya lagi” Ay Tjoe menyahut. “Aku hampir tidak bisa tidur lantaran anak-anak terlalu ribut, setiap menit mesti ada yang berkelahi, menagnis, bersorak atau menjerit. Setiap hari mesti masak nasi dua gantang, dan setiap aku pergi selalu dikerubungi oleh ini anak-anak. Pohon jeruk dan rambutan sampai gundul disenggetin, anak-anak ini kelewat nakal” Meski mulutnya seperti mengomel, tapi Ay Tjoe mengucapkannya dengan tersenyum dan air muka terang, satu tanda hatinya merasa senang.
“Senang sekali melihat semua orang berkumpul di sini” aku berkata, “sebab nati malam tahun baru di sini akan jadi ramai, tidak seperti tahun yang lalu tidak ada satupun yang muncul” “Ya benar, sungguh kebetulan sekali” kata Ay Tjoe sambil tertawa. “Aku sendiri tidak mengira tahun ini semuanya bisa berkumpul jadi satu di rumah ini. Memang tidak enak sekali kalau mesti alami kesunyian seperti tahun lalu” “Kalau begitu, nanti di Pasar Malam kau mesti belanja banyak; beli ikan bandeng sedikitnya satu lusin, dan petasan sepuluh gulung besar” aku menggoda.
“Oh, jangan kuatir” ia menyahut dengan sungguh-sungguh. “Istriku baru buka celengannya dari uang penjualan telur. Tahun ini ada hampir dua ratus perak. Ini semua bakal dipakai buat merayakan tahun baru. Tidak apa, kita royal satu tahun sekali, sebab sekarang aku, anak-anak dan cucu sudah selamet bisa kumpul di sini”.
Ay Tjoe kelihatan tidak merasa jengkel atau khawatir beberapa dari anak-anaknya belum mendapat pekerjaan, karena katanya sekarang harga beras dan makanan lain serba murah dan ia masih mampu memberi makan mereka semua. Sebaliknya ia merasa sangat girang dan bangga karena bisa merayakan tahun baru dengan anak dan cucunya, yang mana kalau bukan merupakan berkah dari masa krisis, pastilah tidak akan terjadi.
